Kasus-kasus yang dinilai publik sebagai tindakan intoleran, hampir selalu muncul di bulan Ramadhan. Selain aksi sweeping oleh ormas, operasi penutupan dan penggrebekan warung makan siang hari oleh sejumlah pemerintah daerah juga menjadi sasaran kritik. Berbagai regulasi dan imbauan yang dijadikan landasan pun dituduh menyimpang dari prinsip kehidupan sosial yang plural dan multikultural.
Akibatnya, sakralitas Ramadhan yang sejatinya damai dalam kekhusyukan ritual, bahkan melimpahkan kebaikan yang luas, seakan berubah menjadi bulan langganan konflik. Dalam konteks itulah terus diperlukan edukasi bahwa kerukunan hanya bisa diwujudkan jika pihak-pihak yang berbeda dengan penuh kesadaran bisa saling bertoleransi. Menghargai, menghormati, dan memberi ruang eksis kepada pihak lain mutlak dilakukan secara dua arah.
Artinya, kebersamaan yang harmoni tidak bisa hanya menuntut untuk “bijak-sana”, tetapi juga dituntut harus “bijak-sini”. Toleransi timbal balik atau resiprokal yang muncul dari kesadaran etika sosial inilah sesungguhnya yang dibutuhkan di tengah heterogenitas bangsa ini.
Beragama di Ruang Publik
Kesepakatan luhur untuk hidup bersama dalam keragaman dan perbedaan, harus disertai dengan kesadaran mendalam tentang ruang privat dan ruang publik. Kebebasan beragama dan berkeyakinan maupun memahami dan melaksanakannya dalam lingkup personal, seutuhnya menjadi hak pribadi yang absolut. Hak yang bersifat non-derogable ini tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apa pun. Ia berada pada ranah privat sebagai forum internum, dan karenanya bersifat bebas tak terbatas.
Tetapi, wujud atau manifestasinya di depan umum akan terbatasi oleh kebebasan orang lain. Keyakinan individu yang diekspresikan di ruang publik beralih menjadi tindakan sosial dan berada di forum externum. Ruang bersama yang berisi warga beragam dan berbeda ini tentu saja harus diatur, dibatasi, dalam rangka perlindungan, ketertiban, dan keamanan umum, moral, serta hak dasar orang lain. Di ruang publik ini setiap orang memiliki hak yang sama dan posisi setara, sehingga tidak ada dominasi baik secara individual maupun komunal.
Dalam konteks Ramadhan, selain berpuasa adalah ritual penting bagi muslim, bulan ini juga diyakini suci, sakral, mulia, sehingga bernilai tinggi secara spiritual. Relevan dengan itu, pelaku puasa berhak beribadah dengan tenang, tidak diganggu, dan tidak direndahkan keyakinannya. Ia berhak atas penghormatan sosial seperti tidak makan minum secara demonstratif untuk provokatif, tidak mengejek praktik puasa, dan hak mendapatkan empati.
Meski demikian, perlu digaris bawahi bahwa hak untuk dihormati sama sekali tidak dalam konteks mengontrol semua orang di ruang publik. Bagi yang tidak berpuasa, baik karena keyakinan maupun faktor lain, juga memiliki hak privacy untuk makan minum dan menggunakan ruang publik secara sah. Negara dan warga tidak bisa memaksa untuk beribadah, maupun tidak beribadah. Karena itu, kehadiran negara dengan regulasi dan penegakannya hanya dalam konteks menjaga ketertiban umum untuk menghindari perbenturan dua hak konstitusional yang berbeda. Selain tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan lebih tinggi, regulasi harus proporsional, tidak diskriminatif, apalagi memaksakan norma mayoritas melalui sanksi.
Toleransi Resiprokal Berbasis Etika Sosial
Jalan tengah yang ditempuh sejumlah pemerintah daerah selama ini dalam menyikapi Ramadhan di tengah keragaman, sejatinya mempraktekkan toleransi resiprokal yang timbal balik dua arah. Mengatur jam operasional rumah makan dan warung kuliner, melengkapi dengan pembatas tirai, mengatur lokasi khusus, dan seterusnya, adalah contoh-contoh riil jalan tengah yang bisa dilakukan. Dengan begitu, di satu sisi pelaku puasa tetap bisa beribadah dengan baik, dan di sisi lain mereka yang tidak berpuasa tetap terpenuhi hak dasarnya untuk makan dan minum.
Negara telah hadir mencegah konflik dan melindungi warganya, baik yang berpuasa maupun yang tidak. Pendekatan dilakukan secara proaktif, persuasif, dan edukatif, bukan razia agresif secara represif, mempermalukan dan merendahkan martabat warga, maupun diskriminatif minoritas. Warga pun diharapkan dengan kesadaran tinggi secara timbal balik saling bertoleransi.
Kehadiran negara untuk menegakkan hak konstitusional warga secara yuridis memang mutlak, namun poin penting sesungguhnya terletak pada perspektif moral, yakni kesadaran bersama untuk beretika sosial di ruang publik. Jika hukum menyoal apa yang boleh dan apa yang tidak secara formal, maka etika sosial lebih dalam dan fundamental, karena mempertimbangkan sensitivitas dan kepatutan. Meski hukum tidak memberi sanksi bagi orang yang makan di dekat pelaku puasa, tetapi secara etika sosial tindakan itu jelas indikasi nihilnya penghormatan dan empati di ranah kebersamaan. Kesadaran moral, nilai-nilai, dan norma yang hidup di masyarakat, mesti ditumbuhkan kembangkan dalam setiap diri individu, agar sensitivitas sosial bisa menopang pendekatan yuridis hukum yang terbatas dan cenderung kaku.
Sebagai energi kohesi komunitas yang beragam dan berbeda, konstruk moral sosial bisa dibangun melalui dialog lintas kelompok. Dengan diskusi timbal balik dua arah, maka akan terbuka sekat pemisah sehingga masing-masing bisa mengenal dengan jernih apa yang sakral-profan, patut-tidak patut, maupun tabu dan terlarang. Begitu juga memahami dengan benar konsep-konsep orang lain, hingga terbangun empati yang tidak hanya memberi ruang bagi orang lain yang berbeda, tetapi turut merasakan apa yang tengah dirasakan orang lain dalam kondisi yang sama. Dengan demikian, pada akhirnya tanpa kehadiran negara pun, dengan kesadaran mendalam masyarakat tetap bisa hidup aman, damai, harmonis, dan rukun dalam keragaman dan perbedaan. Mari berpuasa dengan kemampuan pengendalian diri yang semakin dewasa. Wallahu a’lam!
*Penulis: Faisal Zaini Dahlan (Dosen UIN IB Padang)
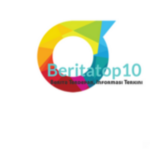
 19 hours ago
13
19 hours ago
13















































